To 3G or Not to 3G
Seandainya William Shakespeare masih hidup dan berlatar belakang insinyur seperti saya, ada kemungkinan dia akan melontarkan kalimat: To 3G or Not to 3G, that is the question.
Kekacauan yang timbul dari implementasi 3G (baca: triji) di beberapa negara Eropa, khususnya Inggris dan Jerman telah menimbulkan banyak spekulasi mengenai kegagalan teknologi ini. Kemudian, diliriklah teknologi nirkabel lainnya, yaitu WiFi sebagai salah satu solusinya. Tidak mengherankan, kalau Pak Onno Purbo mengatakan bahwa WiFi telah memenangkan ‘peperangan’, mengalahkan 3G di kawasan Eropa (Kompas, 30 Mei 2005).
Sekilas 3G
Sejarah mengenai perkembangan 3G berawal dari pembentukan 3GPP (3G Partnership Project) untuk mengembangkan GSM (digital, low speed) menjadi 3G (digital, broadband). Namun, karena lambatnya pengembangan standar di 3GPP, maka berdirilah satu organisasi lagi, yaitu 3GPP2 yang sejak awal mengembangan teknologi 3G berbasis spread spectrum, yang disebut Code Division Multiple Access (GSM menggunakan Time-based dan sinyal tidak disebar (spreaded) di spektrum frekuensi.
Saya percaya bahwa sebuah teknologi hanyalah salah satu faktor saja. Tidak sedikit perusahaan yang mengusung teknologi terbaru yang juga gagal. Contohnya adalah Global Crossing yang mengaklamasi dirinya sebagai MPLS Provider terbesar di dunia, yang mengajukan Chapter 11 (bankruptcy) di Amerika. Hal yang sama juga pernah terjadi pada teknologi ATM (Asynchronous Transfer Mode) yang menjanjikan network yang jauh lebih baik daripada TCP/IP, namun tidak bisa mencapai skala implementasi yang signifikan.
Pada saat ini, saya melihat adanya kebingungan di masyarakat mengenai implementasi dari teknologi 3G ini.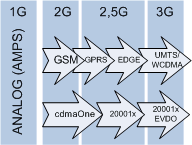 Banyak yang berpikiran bahwa dengan membeli handset 3G, maka akan bisa mendapatkan layanan 3G, padahal tanpa adanya 3G coverage, kemampuan 3G di dalam handset tersebut akan percuma saja. Secara definisi, , ITU mendefinisikan 3G sebagai layanan nirkabel (wireless) yang mampu memberikan kecepatan 144Kbps hingga 2Mbps (tergantung kondisi mobilitas si pelanggan). Dalam pengertian yang lebih umum, 3G adalah generasi di mana multimedia service (seperti layanan video streaming) dapat diakomodir; hal ini hanya bisa terjadi dengan pita lebar (broadband). Untuk itu, 3G adalah layanan nirkabel dengan pita lebar, sedangkan kecepatan yang menengah (±150Kbps) dianggap sebagai transisi menuju 3G.
Banyak yang berpikiran bahwa dengan membeli handset 3G, maka akan bisa mendapatkan layanan 3G, padahal tanpa adanya 3G coverage, kemampuan 3G di dalam handset tersebut akan percuma saja. Secara definisi, , ITU mendefinisikan 3G sebagai layanan nirkabel (wireless) yang mampu memberikan kecepatan 144Kbps hingga 2Mbps (tergantung kondisi mobilitas si pelanggan). Dalam pengertian yang lebih umum, 3G adalah generasi di mana multimedia service (seperti layanan video streaming) dapat diakomodir; hal ini hanya bisa terjadi dengan pita lebar (broadband). Untuk itu, 3G adalah layanan nirkabel dengan pita lebar, sedangkan kecepatan yang menengah (±150Kbps) dianggap sebagai transisi menuju 3G.
Berdasarkan pengertian di atas, maka operator yang menggelar teknologi CDMA 2000 1x pada saat ini, belum bisa dikatakan Operator 3G. Namun keunggulan dari penggunaan CDMA (Code Division Multiple Access) dibandingkan dengan GSM adalah kemampuannya untuk berevolusi dengan mulus. Tidak seperti GSM yang harus mengganti sebagian besar perangkatnya untuk bisa pindah ke domain 3G, operator CDMA dapat menambahkan modul saja.
saat ini, belum bisa dikatakan Operator 3G. Namun keunggulan dari penggunaan CDMA (Code Division Multiple Access) dibandingkan dengan GSM adalah kemampuannya untuk berevolusi dengan mulus. Tidak seperti GSM yang harus mengganti sebagian besar perangkatnya untuk bisa pindah ke domain 3G, operator CDMA dapat menambahkan modul saja.
Pada saat ini, dengan teknologi CDMA 2000 1x RTT (RTT: Radio Transmission Technology, 1x berarti penggunaan Frequency Allocation 1 x 1,25Mhz. CDMA 2000 3xRTT berarti FA: 3 x 1,25 Mhz), saya dapat menggunakan datacard di slot PCMCIA laptop saya untuk terhubung ke Packet Data Network (PDN) dan mengakses Internet secara wireless, di mana pun saya bisa mendapat sinyal dengan baik. Kecepatan akses data PDN yang maksimum mencapai 153 Kbps yang jatuh pada kategori 2,5 G, belum 3G. Sedangkan dari sisi GSM, implementasi GPRS dan EDGE, hingga saat ini, in my humble opinion, belum mencapai hal yang menggembirakan (saya percaya bahwa layanan komunikasi data di GSM akan membaik bila menggunakan 3G). Sedangkan operator baru berbasis CDMA (Flexi, StarOne dan Mobile 8) sudah menawarkan layanan PDN ini dengan gencar.
Teknologi WiFi menggunakan salah satu dari ISM band (Industrial, Scientific and Medical), yaitu: 2,4 Ghz. Band ini, setahu saya, pada awalnya ditujukan untuk keperluan non-komersial oleh Federal Communication Commission (FCC) di AS. Tetapi tidak seperti PDN, di dalam jaringan WiFi tidak ada hand off (atau hand over). Untuk bisa menggunakan WiFi, seseorang harus diam di satu tempat dan tidak bisa sambil mobile. Juga, di dalam jaringan yang yang tidak teregulasi, penggunaan frekuensi yang sama bisa saling menginterferensi satu dan lainnya. (Saya tidak memungkiri adanya kemungkinan teknologi WiFi peer-to-peer seperti Skype, namun sampai teknologi itu ada, maka dipastikan tidak ada hand off). Juga, saya melihat bahwa WiFi sebelum mencapai cakupan yang luas, sudah mendapat tantangan dari penerus teknologi ini, yaitu WiMAX dan WiBro (Wireless Broadband) yang semuanya sibuk berpacu. Dan bahkan, belum lagi tuntas pengembangan dan implementasi 3G di berbagai negara, NTT Docomo di Jepang telah mengembangan sebuah teknologi proprietary, berbasiskan spread spectrum, yang disebut MiMO (Multiple Input, Multiple Output), sebagai layanan 4G, yang mampu memberikan throughput hingga 1 Gbps.
Kalau saja teknologi 3G dikatakan gagal karena tidak mampu memberikan kecepatan yang cukup, hal ini memerlukan penelitian yang lebih jauh lagi, karena bila menyangkut real throughput, banyak hal yang terkait di dalamnya. Seperti: interkoneksi (backbone bottleneck), RF engineering (cell breathing, pilot pollution), kondisi server (apakah sibuk) dan juga keterbatasan dari handset (computing power dan memori) tersebut. Saya sendiri pernah melakukan uji coba file transfer PC-ke-PC, dengan menggunakan jaringan berbasis Fast Ethernet yang mampu mencapai kecepatan 100 Mbps, namun dalam percobaan tersebut hanya bisa mendapatkan 2,5 Mbps, maksimum. Apakah berarti teknologi Fast Ethernet gagal? Keliatannya tidak. Intinya, kita tidak perlu over reacting atas sebuah teknologi, karena masih ada faktor lain penentu kesuksesannya.
Up Front Fee dan Kegagalan 3G
Salah satu faktor pemicu kurang berhasilnya implementasi 3G di Eropa menurut pendapat saya adalah tingginya biaya sewa frekuensi yang harus dibayar di muka (up front fee). Karena terlalu mahalnya biaya tersebut, bahkan ada operator yang mundur dari lelang frekuensi (kasus WorldCom mundur dari lelang frekuensi di Jerman). Operator di Eropa menghadapi dilema yang pelik: bila mereka tidak membeli frekuensi 3G maka pasar saham akan menghancurkan market value perusahaannya, namun bila membayar up front fee, sudah bisa dipastikan bahwa keuangan mereka akan bleeding untuk sekian belas tahun ke depan. Pengembalian lisensi 3G oleh PT. Wireless Indonesia Network (WIN) kepada pemerintah bisa menjadi sinyal awal betapa beratnya bagi operator baru untuk menggelar 3G (walau pun operator incumbent mengalami hal yang berat juga dalam mengimplementasikannya).
Pemerintah Indonesia bisa belajar dari kasus 3G di Eropa (Jerman dan Inggris) dan membandingkannya dengan Jepang. Tidak seperti di Eropa, Operator 3G di Jepang tidak dikenakan up front fee; biaya frekuensi dikenakan berdasarkan pola kegunaan (merit based). Dengan pola ini, operator dikanakan biaya US$ 5 / pelanggan / tahun. Bila dihitung, NTT DoCoMo yang memiliki 30 juta pelanggan, harus membayar US$153 juta tiap tahunnya. Sebuah nilai yang cukup kecil bila dibandingkan dengan biaya frekuensi di Eropa. Tidak perlu diherankan bahwa implementasi 3G di Jepang lebih sukses daripada di Eropa.
Perbandingan Biaya Frekuensi 3G di Beberapa Negara
Sumber: 3G News Room, 2001
Metode lisensi frekuensi di Jepang memberikan kesempatan bagi operator untuk membangun infrastruktur terlebih dahulu dan membayar pemakaian frekuensi belakangan. Sedangkan mekanisme di Eropa, memaksa operator untuk membayar mahal di muka, kemudian membangun infrastruktur (yang juga mahal), sehingga tidak heran bahwa bukan kompetisi yang didapat, tetapi beberapa operator bergabung, berkolaborasi untuk membeli pita frekuensi. Dengan demikian, masuknya asing di dalam kepemilikan calon operator 3G di Indonesia dapat dipahami.
Pemerintah, dalam beberapa kesempatan telah menentukan target untuk mendapatkan Rp. 5 Triliun (atau setara dengan ± US$ 500 juta), sebenarnya suatu jumlah yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan negara Korea Selatan, misalnya. Namun yang perlu diingat adalah bahwa tidak seperti Jepang atau Korea Selatan yang sesama Asia, pendapatan per kapita Indonesia dan penyebaran kemakmuran di Indonesia masih jauh dari istilah bagus. Kasus kekurangan gizi, banyaknya putus sekolah karena tidak ada biaya yang banyak diberitakan oleh media massa bisa dijadikan bukti, bahwa telah terjadi jurang yang makin lebar antara si kaya dan si miskin.
Peranan Pemerintah
Dengan demikian, saya melihat bahwa masalah 3G ini bukan sekedar masalah teknologi, tetapi sangat erat kaitannya dengan regulasi. Bila operator dikenakan up front fee yang besar (guna memicu pendapatan negara), maka operator akan membebankan biaya ini kepada konsumennya. Tidak seperti bisnis handset, dimana konsumen bersedia membayar harga yang mahal untuk sebuah handset yang fitur-nya pun jarang dipakai, konsumen selalu mencari tarif telepon yang murah. Operator yang membayar lisensi pun akan bleeding selama beberapa tahun ke depan, yang akan sangat memberatkan operator tersebut. Sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika oleh Paul A. David menunjukkan bahwa sebuah teknologi infrastruktur akan memberikan keuntungan secara makro, bila deployment dari teknologi tersebut telah mencapai penetrasi minimal 50% dari total populasi. Hal ini terjadi pada industri listrik, telepon, PC dan terakhir Internet. Dibutuhkan waktu 35 tahun bagi Internet untuk mencapai penetrasi lebih dari 50% di AS. Dan usaha Pemerintah AS untuk mendorong baik perkembangan mau pun penetrasi infrastruktur ini dapat terlihat dengan nyata (pada awalnya, TCP/IP bahkan ditujukan untuk pertahanan nasional). Melihat betapa rendahnya penetrasi telekomunikasi di Indonesia, maka Pemerintah sudah selayaknya serius memikirkan hal ini dengan menjadi mampu menjadi pendorong agar penerapan teknologi entah itu 3G maupun wireless lainnya (WiFi, WiMAX, WiBro) dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, adalah baik bila pemerintah mengakomodasi baik unlicensed band dan spektrum berlisensi lainnya, sambil mendorong terjadinya kompetisi yang sehat.
Kekacauan yang timbul dari implementasi 3G (baca: triji) di beberapa negara Eropa, khususnya Inggris dan Jerman telah menimbulkan banyak spekulasi mengenai kegagalan teknologi ini. Kemudian, diliriklah teknologi nirkabel lainnya, yaitu WiFi sebagai salah satu solusinya. Tidak mengherankan, kalau Pak Onno Purbo mengatakan bahwa WiFi telah memenangkan ‘peperangan’, mengalahkan 3G di kawasan Eropa (Kompas, 30 Mei 2005).
Sekilas 3G
Sejarah mengenai perkembangan 3G berawal dari pembentukan 3GPP (3G Partnership Project) untuk mengembangkan GSM (digital, low speed) menjadi 3G (digital, broadband). Namun, karena lambatnya pengembangan standar di 3GPP, maka berdirilah satu organisasi lagi, yaitu 3GPP2 yang sejak awal mengembangan teknologi 3G berbasis spread spectrum, yang disebut Code Division Multiple Access (GSM menggunakan Time-based dan sinyal tidak disebar (spreaded) di spektrum frekuensi.
Saya percaya bahwa sebuah teknologi hanyalah salah satu faktor saja. Tidak sedikit perusahaan yang mengusung teknologi terbaru yang juga gagal. Contohnya adalah Global Crossing yang mengaklamasi dirinya sebagai MPLS Provider terbesar di dunia, yang mengajukan Chapter 11 (bankruptcy) di Amerika. Hal yang sama juga pernah terjadi pada teknologi ATM (Asynchronous Transfer Mode) yang menjanjikan network yang jauh lebih baik daripada TCP/IP, namun tidak bisa mencapai skala implementasi yang signifikan.
Pada saat ini, saya melihat adanya kebingungan di masyarakat mengenai implementasi dari teknologi 3G ini.
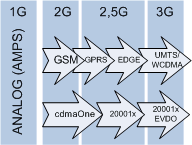 Banyak yang berpikiran bahwa dengan membeli handset 3G, maka akan bisa mendapatkan layanan 3G, padahal tanpa adanya 3G coverage, kemampuan 3G di dalam handset tersebut akan percuma saja. Secara definisi, , ITU mendefinisikan 3G sebagai layanan nirkabel (wireless) yang mampu memberikan kecepatan 144Kbps hingga 2Mbps (tergantung kondisi mobilitas si pelanggan). Dalam pengertian yang lebih umum, 3G adalah generasi di mana multimedia service (seperti layanan video streaming) dapat diakomodir; hal ini hanya bisa terjadi dengan pita lebar (broadband). Untuk itu, 3G adalah layanan nirkabel dengan pita lebar, sedangkan kecepatan yang menengah (±150Kbps) dianggap sebagai transisi menuju 3G.
Banyak yang berpikiran bahwa dengan membeli handset 3G, maka akan bisa mendapatkan layanan 3G, padahal tanpa adanya 3G coverage, kemampuan 3G di dalam handset tersebut akan percuma saja. Secara definisi, , ITU mendefinisikan 3G sebagai layanan nirkabel (wireless) yang mampu memberikan kecepatan 144Kbps hingga 2Mbps (tergantung kondisi mobilitas si pelanggan). Dalam pengertian yang lebih umum, 3G adalah generasi di mana multimedia service (seperti layanan video streaming) dapat diakomodir; hal ini hanya bisa terjadi dengan pita lebar (broadband). Untuk itu, 3G adalah layanan nirkabel dengan pita lebar, sedangkan kecepatan yang menengah (±150Kbps) dianggap sebagai transisi menuju 3G.Berdasarkan pengertian di atas, maka operator yang menggelar teknologi CDMA 2000 1x pada
 saat ini, belum bisa dikatakan Operator 3G. Namun keunggulan dari penggunaan CDMA (Code Division Multiple Access) dibandingkan dengan GSM adalah kemampuannya untuk berevolusi dengan mulus. Tidak seperti GSM yang harus mengganti sebagian besar perangkatnya untuk bisa pindah ke domain 3G, operator CDMA dapat menambahkan modul saja.
saat ini, belum bisa dikatakan Operator 3G. Namun keunggulan dari penggunaan CDMA (Code Division Multiple Access) dibandingkan dengan GSM adalah kemampuannya untuk berevolusi dengan mulus. Tidak seperti GSM yang harus mengganti sebagian besar perangkatnya untuk bisa pindah ke domain 3G, operator CDMA dapat menambahkan modul saja.Pada saat ini, dengan teknologi CDMA 2000 1x RTT (RTT: Radio Transmission Technology, 1x berarti penggunaan Frequency Allocation 1 x 1,25Mhz. CDMA 2000 3xRTT berarti FA: 3 x 1,25 Mhz), saya dapat menggunakan datacard di slot PCMCIA laptop saya untuk terhubung ke Packet Data Network (PDN) dan mengakses Internet secara wireless, di mana pun saya bisa mendapat sinyal dengan baik. Kecepatan akses data PDN yang maksimum mencapai 153 Kbps yang jatuh pada kategori 2,5 G, belum 3G. Sedangkan dari sisi GSM, implementasi GPRS dan EDGE, hingga saat ini, in my humble opinion, belum mencapai hal yang menggembirakan (saya percaya bahwa layanan komunikasi data di GSM akan membaik bila menggunakan 3G). Sedangkan operator baru berbasis CDMA (Flexi, StarOne dan Mobile 8) sudah menawarkan layanan PDN ini dengan gencar.
Teknologi WiFi menggunakan salah satu dari ISM band (Industrial, Scientific and Medical), yaitu: 2,4 Ghz. Band ini, setahu saya, pada awalnya ditujukan untuk keperluan non-komersial oleh Federal Communication Commission (FCC) di AS. Tetapi tidak seperti PDN, di dalam jaringan WiFi tidak ada hand off (atau hand over). Untuk bisa menggunakan WiFi, seseorang harus diam di satu tempat dan tidak bisa sambil mobile. Juga, di dalam jaringan yang yang tidak teregulasi, penggunaan frekuensi yang sama bisa saling menginterferensi satu dan lainnya. (Saya tidak memungkiri adanya kemungkinan teknologi WiFi peer-to-peer seperti Skype, namun sampai teknologi itu ada, maka dipastikan tidak ada hand off). Juga, saya melihat bahwa WiFi sebelum mencapai cakupan yang luas, sudah mendapat tantangan dari penerus teknologi ini, yaitu WiMAX dan WiBro (Wireless Broadband) yang semuanya sibuk berpacu. Dan bahkan, belum lagi tuntas pengembangan dan implementasi 3G di berbagai negara, NTT Docomo di Jepang telah mengembangan sebuah teknologi proprietary, berbasiskan spread spectrum, yang disebut MiMO (Multiple Input, Multiple Output), sebagai layanan 4G, yang mampu memberikan throughput hingga 1 Gbps.
Kalau saja teknologi 3G dikatakan gagal karena tidak mampu memberikan kecepatan yang cukup, hal ini memerlukan penelitian yang lebih jauh lagi, karena bila menyangkut real throughput, banyak hal yang terkait di dalamnya. Seperti: interkoneksi (backbone bottleneck), RF engineering (cell breathing, pilot pollution), kondisi server (apakah sibuk) dan juga keterbatasan dari handset (computing power dan memori) tersebut. Saya sendiri pernah melakukan uji coba file transfer PC-ke-PC, dengan menggunakan jaringan berbasis Fast Ethernet yang mampu mencapai kecepatan 100 Mbps, namun dalam percobaan tersebut hanya bisa mendapatkan 2,5 Mbps, maksimum. Apakah berarti teknologi Fast Ethernet gagal? Keliatannya tidak. Intinya, kita tidak perlu over reacting atas sebuah teknologi, karena masih ada faktor lain penentu kesuksesannya.
Up Front Fee dan Kegagalan 3G
Salah satu faktor pemicu kurang berhasilnya implementasi 3G di Eropa menurut pendapat saya adalah tingginya biaya sewa frekuensi yang harus dibayar di muka (up front fee). Karena terlalu mahalnya biaya tersebut, bahkan ada operator yang mundur dari lelang frekuensi (kasus WorldCom mundur dari lelang frekuensi di Jerman). Operator di Eropa menghadapi dilema yang pelik: bila mereka tidak membeli frekuensi 3G maka pasar saham akan menghancurkan market value perusahaannya, namun bila membayar up front fee, sudah bisa dipastikan bahwa keuangan mereka akan bleeding untuk sekian belas tahun ke depan. Pengembalian lisensi 3G oleh PT. Wireless Indonesia Network (WIN) kepada pemerintah bisa menjadi sinyal awal betapa beratnya bagi operator baru untuk menggelar 3G (walau pun operator incumbent mengalami hal yang berat juga dalam mengimplementasikannya).
Pemerintah Indonesia bisa belajar dari kasus 3G di Eropa (Jerman dan Inggris) dan membandingkannya dengan Jepang. Tidak seperti di Eropa, Operator 3G di Jepang tidak dikenakan up front fee; biaya frekuensi dikenakan berdasarkan pola kegunaan (merit based). Dengan pola ini, operator dikanakan biaya US$ 5 / pelanggan / tahun. Bila dihitung, NTT DoCoMo yang memiliki 30 juta pelanggan, harus membayar US$153 juta tiap tahunnya. Sebuah nilai yang cukup kecil bila dibandingkan dengan biaya frekuensi di Eropa. Tidak perlu diherankan bahwa implementasi 3G di Jepang lebih sukses daripada di Eropa.
Perbandingan Biaya Frekuensi 3G di Beberapa Negara
| Negara | Tot. Up Front Fee | Jml. Operator |
|---|---|---|
| Jerman | US $46,1 Miliar | 6 |
| Inggris | US$ 35,4 Miliar | 5 |
| Korsel | US$ 3,3 Miliar | 3 |
| Singapura | US$ 165,8 Juta | 3 |
| Jepang | Tidak Ada | 3 |
Sumber: 3G News Room, 2001
Metode lisensi frekuensi di Jepang memberikan kesempatan bagi operator untuk membangun infrastruktur terlebih dahulu dan membayar pemakaian frekuensi belakangan. Sedangkan mekanisme di Eropa, memaksa operator untuk membayar mahal di muka, kemudian membangun infrastruktur (yang juga mahal), sehingga tidak heran bahwa bukan kompetisi yang didapat, tetapi beberapa operator bergabung, berkolaborasi untuk membeli pita frekuensi. Dengan demikian, masuknya asing di dalam kepemilikan calon operator 3G di Indonesia dapat dipahami.
Pemerintah, dalam beberapa kesempatan telah menentukan target untuk mendapatkan Rp. 5 Triliun (atau setara dengan ± US$ 500 juta), sebenarnya suatu jumlah yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan negara Korea Selatan, misalnya. Namun yang perlu diingat adalah bahwa tidak seperti Jepang atau Korea Selatan yang sesama Asia, pendapatan per kapita Indonesia dan penyebaran kemakmuran di Indonesia masih jauh dari istilah bagus. Kasus kekurangan gizi, banyaknya putus sekolah karena tidak ada biaya yang banyak diberitakan oleh media massa bisa dijadikan bukti, bahwa telah terjadi jurang yang makin lebar antara si kaya dan si miskin.
Peranan Pemerintah
Dengan demikian, saya melihat bahwa masalah 3G ini bukan sekedar masalah teknologi, tetapi sangat erat kaitannya dengan regulasi. Bila operator dikenakan up front fee yang besar (guna memicu pendapatan negara), maka operator akan membebankan biaya ini kepada konsumennya. Tidak seperti bisnis handset, dimana konsumen bersedia membayar harga yang mahal untuk sebuah handset yang fitur-nya pun jarang dipakai, konsumen selalu mencari tarif telepon yang murah. Operator yang membayar lisensi pun akan bleeding selama beberapa tahun ke depan, yang akan sangat memberatkan operator tersebut. Sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika oleh Paul A. David menunjukkan bahwa sebuah teknologi infrastruktur akan memberikan keuntungan secara makro, bila deployment dari teknologi tersebut telah mencapai penetrasi minimal 50% dari total populasi. Hal ini terjadi pada industri listrik, telepon, PC dan terakhir Internet. Dibutuhkan waktu 35 tahun bagi Internet untuk mencapai penetrasi lebih dari 50% di AS. Dan usaha Pemerintah AS untuk mendorong baik perkembangan mau pun penetrasi infrastruktur ini dapat terlihat dengan nyata (pada awalnya, TCP/IP bahkan ditujukan untuk pertahanan nasional). Melihat betapa rendahnya penetrasi telekomunikasi di Indonesia, maka Pemerintah sudah selayaknya serius memikirkan hal ini dengan menjadi mampu menjadi pendorong agar penerapan teknologi entah itu 3G maupun wireless lainnya (WiFi, WiMAX, WiBro) dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, adalah baik bila pemerintah mengakomodasi baik unlicensed band dan spektrum berlisensi lainnya, sambil mendorong terjadinya kompetisi yang sehat.


0 Comments:
Post a Comment
<< Home